Seribu Kanal Membelah Dam
 Sepi menyelimuti Staanplaat Amstel, Amsterdam. Tak seperti terminal Pulogadung, yang diramaikan teriakan calo. Juga tak ada bau pesing penanda terminal atau tempat publik yang kenyamanannya di nomor-sekiankan. Setelah membersih diri sisa perjalanan semalaman dari London, kami bergegas ke spoor station yang bersisian dengan stallplaat. Tujuan pagi ini adalah centrum kota Amsterdam. Seorang nenek yang aku bagi tempat duduk mengajakku bicara. Melihatku bingung, seorang lelaki paruh baya menyambung dengan bahasa Indonesia logat aneh: "Ia bilang, ramai sekali". Godverdomme, tampang melayu memang mudah ditemui disini.
Sepi menyelimuti Staanplaat Amstel, Amsterdam. Tak seperti terminal Pulogadung, yang diramaikan teriakan calo. Juga tak ada bau pesing penanda terminal atau tempat publik yang kenyamanannya di nomor-sekiankan. Setelah membersih diri sisa perjalanan semalaman dari London, kami bergegas ke spoor station yang bersisian dengan stallplaat. Tujuan pagi ini adalah centrum kota Amsterdam. Seorang nenek yang aku bagi tempat duduk mengajakku bicara. Melihatku bingung, seorang lelaki paruh baya menyambung dengan bahasa Indonesia logat aneh: "Ia bilang, ramai sekali". Godverdomme, tampang melayu memang mudah ditemui disini.
Keluar di centraal station, pandanganku menyapu hotel Batavia. Entah ini sekedar mengenang tanah jajahan, atau untuk "penghargaan" tenaga yang diperas untuk rodi dan kultur stelsel abad silam nan kelam. Aku susuri jalan raya Damrak Straat, yang sedang marak menggelar korting summer. Disini menyeberang harus penuh kehati-hatian. Sebab jalan ini meladeni tiga moda kenderaan, mobil, trem, dan sepeda. Kami hanyut bersama arus orang yang bermuara di Koninklijk Paleis. Di depan balikota ini, beberapa orang memajang diri dengan kostum serdadu jaman baheula atau none Belande, dan meminta duit sebelum dipotret.
Lelah berkeliling, lapar pun mulai mengganggu. Kata kunci yang diberikan Lely untuk makan enak, adalah "Zeedijk" dan "New King". Bau masakan dengan bumbu menyengat segera menyergap. Ada bakso, nasi goreng warna kehitaman --mungkin digoreng diatas belanga hitam legam khas restoran Cina--, dan ikan goreng dengan bumbu mlekoh. Zeedijk Straat juga menyediakan tontonan menarik dalam etalase, khas kawasan merah.
Ketika rintik hujan menyentuh bumi, kami putuskan untuk menyusuri sungai naik kanaal bus. Amsterdam memang dikenal sebagai negeri seratus kanal. Rakit bermesin itu pun meluncur menyuruk jembatan, yang jumlahnya di seluruh kota hampir seribu. Panjang seluruh kanal buatan sejak abad XVII ini, mencapai 100 kilometer, dibangun untuk mengatasi banjir, karena permukaan tanah berada dibawah permukaan laut.
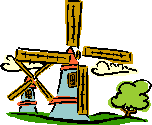 Sehabis berlayar, sedianya kami akan ke Vondelpark, taman seluas 48 hektar yang menjadi paru-paru kota, yang mengingatkan pada Kebun Raya di Buitenzorg sana. Karena sudah lelah, kami putuskan tidak pergi, tapi duduk menyesap thee dan koffie di cafe pinggir jalan, sambil menatap none-none yang ngebut bersepeda ontel disisi trem. Aku berdoa, semoga tidak bertemu anggota dewan yang sedang studi banding kesini. Sebab aku takut rasa hormatku kepada wakil rakyat itu memudar. Karena menurut hematku, yang harus dikirim studi banding itu adalah pegawai kereta api (mempelajari sistem trem), penata kota (belajar menyediakan lalulintas yang ramah buat pejalan kaki (voet) dan sepeda (fiets)), serta pegawai PU, untuk belajar mengatasi banjir.
Sehabis berlayar, sedianya kami akan ke Vondelpark, taman seluas 48 hektar yang menjadi paru-paru kota, yang mengingatkan pada Kebun Raya di Buitenzorg sana. Karena sudah lelah, kami putuskan tidak pergi, tapi duduk menyesap thee dan koffie di cafe pinggir jalan, sambil menatap none-none yang ngebut bersepeda ontel disisi trem. Aku berdoa, semoga tidak bertemu anggota dewan yang sedang studi banding kesini. Sebab aku takut rasa hormatku kepada wakil rakyat itu memudar. Karena menurut hematku, yang harus dikirim studi banding itu adalah pegawai kereta api (mempelajari sistem trem), penata kota (belajar menyediakan lalulintas yang ramah buat pejalan kaki (voet) dan sepeda (fiets)), serta pegawai PU, untuk belajar mengatasi banjir.
Malam pun turun. Kami bergegas kembali ke Amstal, mengejar bus menuju Paris. Tot ziens, Amsterdam.


3 Comments:
Wakil rakyat dan para birokrat, meski acapkali sasaran sindirian dari yang halus sampai kasarpun, kalau hatinya udah bisu-budeg-dan basi, susah, man! :), study tour atau studi banding-entah apalah namanya itu, mudah2an bukan cuman judulnya aja..
Seneng udah bisa mampir kesini..salam kenal danslam hangat dari Monrovia! :D
mudah2an studinya bukan utk membandingkan cara efektif menyedot uang rakyat. seperti dulu voc dan kompeni lakukan. eyang tak perlu minder jalan2 di jalan dan menyusuri kanal2... kan uang leluhur kit ayg dipakai mbangun jalan, kanal, gedung dan taman itu. jadi ada hak kita utk memakainya..
bagus sekali info nya sangat menarik penuh inspirasi
terimakasih
Post a Comment
<< Home